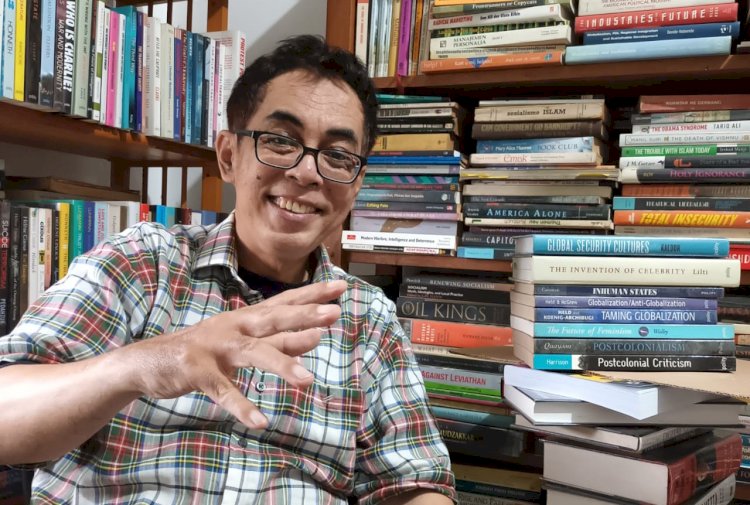- Berkat Mahadata plus Akal Imitasi, Riset Jadi Mudah
- Iran Pionir Poros Perlawanan
- Rasisme Kulit Putih di Balik Trump
SUMBER politik kebangsaan kita adalah Sumpah Pemuda 1928. Ketika para pemuda dan pemudi berkumpul di Batavia (kini Jakarta) pada 27—28 Oktober 1928 untuk menyatakan tekad bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, Indonesia. Sejak saat itu, deklarasi ini menjadi rujukan nasional penanda kebangkitan.
Sumpah Pemuda terjadi 27 tahun setelah Ratu Belanda Wilhelmina menetapkan kebijakan politik etis pada 17 September 1901. Tak banyak yang melihat kaitan antara kedua momen penting ini. Padahal, kebijakan etis mempunyai pengaruh besar terhadap alam berpikir bumiputera didikan sekolah-sekolah berbahasa Belanda.
Sebelum kebijakan etis diberlakukan, pemerintah kolonial Belanda telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tahun 1818 yang mewajibkan para amtenar Eropa di Hindia-Belanda mempelajari bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa. Pada 25 Maret 1819, gubernur-jenderal Van Capellen bahkan memberi waktu setahun kepada para amtenar Eropa untuk menguasai bahasa daerah, tanpa perlu lagi bantuan penerjemah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah 1818 juga memberi izin kepada pribumi untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Kees Groeneboer dalam bukunya ''Weg tot het Westen (Jalan ke Barat)'' (1993) memaparkan betapa banyak anak-anak pribumi kemudian masuk sekolah-sekolah tersebut. Walaupun kelompok konservatif Belanda menentang aturan itu karena berpendapat izin masuk sekolah bisa merusak pergaulan orang-orang Belanda di tanah Hindia.
Namun, provokasi kaum konservatif Belanda tersingkir setelah Conrad Theodore van Deventer (Ch. Th. van Deventer) menulis artikel bertajuk ''Utang Budi'' dalam jurnal De Gids bulan Agustus 1899. Ditulisnya, pemerintah Belanda telah sengaja memindahkan saldo keuntungan Hindia-Belanda ke kas pemerintah Belanda tapi sengaja membiarkan wilayah Hindia-Belanda terpuruk. Itu penghisapan, sangat tak manusiawi. Parlemen Belanda geger, ujungnya Ratu Wilhelmina menggulirkan kebijakan etis.
Kebijakan Etis Sebagai Biopolitik
Istilah biopolitik pertama kali disebut filsuf Prancis Michel Foucault. Merujuk pada fenomena dampak kebijakan politik terhadap populasi dan lingkungan dimana populasi itu berada. Foucault melakukan pembacaan seksama situasi Eropa abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Disebut dalam tiga karya hasil kumpulan kuliahnya di Collège de France. Yakni, ‘Society Must be Defended’ (2003), 'Security, Territory Population (2009), dan 'The Birth of Biopolitics' (2008). Bahwa, biopolitik dapat dipahami sebagai rasionalitas politik yang menjadikan pengaturan kehidupan dan populasi sebagai subjeknya. Misalnya, memastikan, menjaga keberlangsungan, serta meningkatkan kehidupan.
Biopolitik tidak hanya berlangsung di Eropa pada abad ke-19, namun juga menulari wilayah koloni nun jauh dari benua biru. Pemerintah kolonial berusaha keras mengatur kehidupan tanah jajahannya sesuai arahan dari negara induk. Biopolitik menandai transformasi sejarah yang signifikan dari politik kedaulatan (sovereignty) menjadi politik masyarakat (society). Oleh karena itu secara genealogis, Foucault membawa kita dari 'kedaulatan yang harus dipertahankan' menjadi - seperti yang ditegaskan dalam seri kuliahnya - 'masyarakat yang kudu dibela'.
Foucault berbicara di sini tentang kekuatan yang secara signifikan memiliki pengaruh positif pada kehidupan. Biopolitik merupakan 'transformasi mendalam dari mekanisme kekuasaan' yang sejauh ini berbeda dari kekuasaan yang represif dan negatif. Memang, Foucault melakukan kritik panjang terhadap fungsi kekuasaan yang represif dalam buku 'The Will to Know' (2013). Dimana ia menunjukkan bahwa kekuasaan represif berfungsi menyembunyikan kapasitas kekuasaan produktif atau 'positif' yang sesungguhnya berperan dalam pemerintahan kapitalis abad ke-19.
Ketika Conrad Theodore van Deventer (Ch. Th. van Deventer) mengkritik sepak-terjang kekuasaan kapitalisme Belanda yang telah menghisap sumberdaya Hindia-Belanda. Maka, tersingkaplah kekuasaan represif cum rakus Belanda yang mengakibatkan lahirnya kebijakan etis. Kebijakan ini kelak sangat berpengaruh pada kesadaran sebagian populasi di Hindia-Belanda.
Ada tiga program kebijakan etis pemerintahan Hindia-Belanda. Selain irigasi dan migrasi, edukasi menjadi program penting lainnya. Wujud program edukasi adalah lebih terbukanya sekolah-sekolah berbahasa pengantar Belanda untuk anak-anak pribumi. Ini pintu masuk jagat literasi. Walaupun sebenarnya Europeesche Lagere School atau ELS sudah lebih dulu eksis di bumi khatulistiwa ini. ELS didirikan tahun 1817. Selanjutnya, pada 1860, Raja Willem III menginstruksikan pemerintah Hindia-Belanda membangun Gymnasium Willem III di Batavia. Raja Willem III adalah ayah dari Ratu Wilhelmina.
Gymnasium Willem III lalu berubah menjadi Hoogere Burgerschool (HBS). Pada 1875 dibuka HBS di Surabaya, lalu HBS di Semarang pada 1877. Peraturan pemerintah kolonial 1892 jo 1989 mendorong dibukanya lebih banyak sekolah berbahasa Belanda di tiap karesidenan dan kawedanan. Sekolah-sekolah ini semula khusus untuk anak-anak Belanda, peranakan Belanda dan anak para priyayi. Belum terbuka untuk pribumi secara keseluruhan. Setelah pemberlakuan kebijakan etis, sekolah-sekolah itu terbuka menerima siswa-siswi pribumi tanpa memandang status sosial.
Dalam keseharian, para siswa-siswi sekolah tersebut terbiasa berbahasa Belanda. Mereka berbincang dalam bahasa Belanda, berkomunikasi antar sesama dalam bahasa tersebut. Bahasa Belanda menjadi bahasa pergaulan remaja bumiputera. Mereka memahami tata bahasa, ekspresi idiomatik serta kolokuial bahasa Belanda dengan baik. Kian lama mereka kian fasih berbahasa Belanda dan mampu masuk ke jagat literasi berbahasa Belanda.
Kesadaran Berbangsa
Sungguh menarik melihat situasi pra-Sumpah Pemuda 1928. Kaum muda terdidik saat itu terbiasa bercakap memakai bahasa Belanda. Bahkan, mereka melahirkan organisasi kepemudaan daerah memakai sebutan Belanda, 'Jong'. Tri Koro Dharmo mengubah diri menjadi 'Jong Java' pada 1918, Jong Sumatra Bond dibentuk 1917, Jong Celebes berdiri pada 1918, Jong Ambon juga berdiri pada 1918. Jong Bataks Bond berdiri pada tahun 1925. Hanya sedikit yang memakai nama daerah, misal Sekar Rukun yang berdiri tahun 1919.
Keseharian berbahasa Belanda telah mengubah daya pikir serta mental pemakainya. Dengan menguasai bahasa penjajah secara baik dan benar, mereka jadi lebih bisa memperluas cakrawala kebudayaan serta peradaban. Dan yang pasti, tak lagi mudah dikibuli mulut manis penjajah. Bahkan, dengan menguasai bahasa Belanda anak-anak bumiputera berhasil masuk ke dunia literasi Barat. Mereka membaca karya-karya sastra Barat sehingga horizon pemikirannya pun kian luas. Bahkan Sjahrir dan sejumlah sohib karibnya membentuk klub debat bernama Latin 'Patriae Scientifiquae' (Sains untuk tanah air) di sekolahnya, AMS C di Bandung, pada tahun 1926.
Rudolf Mrazek mencatat dalam bukunya 'Sjahrir, Politics and Exile in Indonesia' yang terbit tahun 2018. Bahwa Sjahrir bersama 10 orang sobat eratnya di Bandung mendirikan 'Jong Indonesie' pada 20 Februari 1927. Inilah organisasi kepemudaan yang pertama kali memakai nama 'Indonesia' di Hindia-Belanda sehingga membedakannya dari organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan kala itu. Sampai akhir 1928, organisasi 'Jong Indonesie' ini cepat tersebar ke seantero Jawa dan dibentuk pula cabang keputrian 'Poetri Indonesia'.
Suasana mulai berubah menjelang Kongres Pemuda di Batavia 1928. Para remaja bumiputera yang sudah terbiasa berbahasa Belanda, harus mempersiapkan diri berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Dan untuk memenuhi tuntutan harus berbahasa Indonesia ketika dalam acara Sumpah Pemuda di Batavia, sejak Desember 1927 nama 'Jong Indonesie' diubah menjadi 'Pemoeda Indonesia. Dan kewajiban lain adalah mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat-rapat Pemoeda Indonesia.
Sungguh sulit mengubah kebiasaan bercakap-cakap dalam bahasa Belanda mendadak wajib berbahasa Indonesia saat rapat. Ada beberapa peserta rapat, yang baru saja belajar bahasa Indonesia. Mereka berbincang beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia, namun lama-lama balik lagi memakai bahasa Belanda. Mrazek menulis, pengurus Pemoeda Indonesia sampai harus menggelar pelatihan berbahasa Indonesia.
Dari rangkaian peristiwa sejarah ini semoga kita bisa menyegarkan kembali politik kebangsaan kita yang tidak bersifat xenofobia, anti-asing. Bahkan penguasaan bahasa asing para pendiri bangsa yang sangat bagus telah memungkinkan mereka menyerap literatur asing secara baik. Pada ujungnya melahirkan rasa kebangsaan yang kuat, kokoh, mampu memprediksi serta berani tegak menantang berbagai ancaman asing.
Peneliti JPIPNetwork
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Berkat Mahadata plus Akal Imitasi, Riset Jadi Mudah
- Iran Pionir Poros Perlawanan
- Rasisme Kulit Putih di Balik Trump