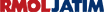 Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari constitutional interpretation. (Craig R. Ducat, 2004). Albert H. Y. Chen, menggunakan istilah constitutional interpretation yang dibedakan dari interpretation of statutes.
Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari constitutional interpretation. (Craig R. Ducat, 2004). Albert H. Y. Chen, menggunakan istilah constitutional interpretation yang dibedakan dari interpretation of statutes.
Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (rechstvinding) berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi (MK). Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.
Satjipto Rahardjo mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya.
Namun demikian, pengutaraan dalam bentuk tulisan atau litera scripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan.
Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undanganyang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk interpretasi atau konstruksi. Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan. (Satjipto Rahardjo, 2006).
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) memeutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar pada hakekatnya adalah kewenangan untuk menafsirkan. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konsitusi diposisikan sebagai the sole interpreter of the constitution.
Hal tersebut cukup mempunyai alasan yang kuat karena penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang dibuat bersifat final and binding.
Keberadaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi merupakan akibat dari perubahan paradigma UUD NRI Tahun 1945 yang tidak lagi menganut sistem pembagian kekuasaan, tetapi pemisahan kekuasaan dengan menerapkan prinsip checks and balances. Masing-masing organ negara dalam kedudukan yang sederajat satu dengan yang lain.
Sebelum UUD NRI Tahun 1945 diubah, paradigma yang dipakai adalah supremacy of parliament dengan menempatkankan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan rakyat. (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan).
Melalui Perubahan Ketiga, kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum merupakan pasangang dari penerapan asas kedaulatan rakyat (demokrasi), sehingga pelaksanaan kedaulatan rakyat akan dikontrol oleh norma-norma hukum, nomokrasi. (Winarno Yudho, 2009).
Lebih lanjut, prinsip kedaulatan rakyat menghendaki keterbukaan (tranparancy) dan tanggung jawab (accountability). Sedangkan prinsip negara hukum menghendaki semua bentuk tindakan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan atasa hukum.
Dua prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara harus tercemin dalam penataan sistem peradilan kita. Kehadiran sebuah komisi yang bersifat mandiri dan diberi wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) merupakan paradigma baru untuk membangun sistem peradilan di Indonesia.
Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman paska-perubahan undang-undanng dasar telah mengalami perubahan. Sebelum perubahan, ketentuan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya terdiri dua pasal, yakni Pasal 24 dan 25. Pasal 24 UUD 1945 sebelum diubah menentukan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undangâ€.
Ketentuan Pasal 24 sebelum diubah berbeda sekali dengan rumusan setelah perubahan. Sebelum perubahan, sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.
Setelah perubahan kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2)). Meskipun sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya terdapat perbedaan.
Mahkamah Agung melaksanakan peradilan untuk menegakkan undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi melaksanakan peradilan untuk menegakkan konstitusi. Karena mempunyai fungsi untuk menegakkan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitution.
Dalam rangka untuk melaksanakan prinsip checks and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk melakukan pengujian terhadap undang-undang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengujian undang-undang merupkan proses penafsiran. Mahkamah Konstitusi akan menguji, apakah suatu undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden itu sesuai atau tidak dengan konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Konstitusionalitas undang-undang yang diperiksa Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir konstitusi yang bersifat mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dalam sidang pleno hakim konstitusi merupakan pendapat Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding dan tidak perlu ada lembaga khusus untuk melaksanakan putusan (eksekusi), karena semua pihak wajib melaksanakan putusan. Putusan mengikat sejak dibacakan dalam sidang pleno hakim konstitusi yang terbuka untuk umum.
Dengan demikian, tidak ada pendapat Mahkamah Konstitusi yang disampaikan di luar persidangan dalam bentuk apa pun selain Putusan. Sejalan dengan itu, maka tidak pernah ada fatwa yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi.
Original Intent?
Perlu untuk diperhatikan adalah, bagaimana penafsiran dilakukan Apakah suatu penafsiran konstitusi itu harus dilakukan berdasarkan prinsip original intent, tekstual ataukah yang bersifat kontekstual. Hal ini, sepenuhnya tergantung dari hakim yang jumlahnya sembilan orang.
Pembicaraan tentang penafsirkan konstitusi apakah harus mengikuti original intent atau tidak, pernah menjadi perdebatan yang hangat di Amerika Serikat. Perdebatan dipicu ketika Attorne General Edwin Meese III berbicara di depan Amarican Bar Association pada bulan Jui tahun 1985. Dalam pidatonya, dia memberikan dukungan terhadap a jurisprudence of original intention.
Dia berpendapat bahwa: The original meaning of constitutional provisions and statutes provided the only reliable guide for judment. Tiga bulan setelah itu Justice William J. Brennen menyatakan, ketidaksetujuannya atas pemikiran Meesee dan para pendukungnya. Dia menyatakan, bahwa penafsiran yang didasarkan pada original intent tidak praktis dan tidak memadai (impractical and inadequate) dan untuk mengetahui secara pasti tentang original intent bukan hal yang mudah. (Winarno Yudho, 2009).
Bagaimana para hakim Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusional dalam perkara pengujian undang-undang, tentunya terpulang dari orientasi para hakim yang berjumlah sembilan orang itu. Jika para hakim berpikiran conservative tentu sependapat dengan Meese, namun jika berpikiran sedikit liberal dan mendukung judicial activism mungkin akan sependapat dengan Jutice William J. Brennen.[...
*) Penulis adalah Pakar Hukum Konstitusi Untag Surabaya dan Pendiri Rumah Dedikasi†Soetanto Soepiadhyikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Bensin Sawit
- State Guarantee untuk Perbaikan Ekonomi Rakyat
- NU dan Dramaturgi Kiai Marzuki Mustamar





