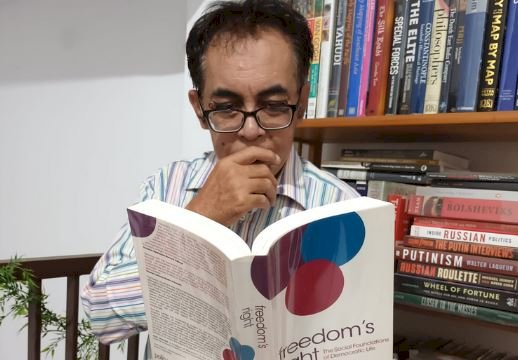SELALU ada yang bisa dipetik sebagai pelajaran dari peristiwa 10 November 1945. Selain beromantika di masa revolusi, tentunya perlu juga merenung kiranya apa saja pelajaran lain dari peristiwa tersebut untuk masa kini. Pelajaran yang juga bermanfaat bukan saja untuk pembangunan serta pengembangan kota Surabaya, melainkan juga bisa menjadi masukan untuk daerah-daerah lain.
Kali ini, tulisan ini ingin melihat peristiwa heroik di kota multi-budaya, multi etnis ini dalam bingkai ''Urban Warfare''. Sebuah bingkai yang belakangan telah ramai diperbincangkan publik internasional berkaitan pada kehadiran aparat keamanan atau pertahanan di tengah-tengah masyarakat.
Selama era kolonial Belanda di Surabaya, kehadiran aparat di tengah masyarakat selalu bermakna semata menegakkan ketertiban, keteraturan serta kepatuhan warga pada aturan-aturan kolonial. Aturan diskriminatif yang dibuat pemerintah kolonial sedemikian rupa yang sesungguhnya sarat ketimpangan serta tak berpihak kepada penduduk asli Surabaya.
Memasuki era pendudukan Jepang sejak 1942, berlaku aturan lebih ketat serta keras di kota Surabaya. Jepang menghendaki mobilisasi massa sekaligus penegakan kedisiplinan. Hubungan warga kepada pemerintahan pendudukan Jepang sama buruknya, bahkan lebih buruk lagi, daripada pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun hubungan ini pelan-pelan berubah begitu Jepang menyerah kepada sekutu.
Tiga tahun kehadiran pendudukan Jepang di kota Surabaya tentu sangat singkat. Namun, ini menjadi babak penting dalam sejarah Surabaya. Selain dikarenakan pemerintahan pendudukan Jepang banyak membentuk badan semimiliter atau pendidikan militer untuk kalangan pemuda, pemerintahan pendudukan Jepang juga membuka akses lebih luas kepada warga untuk masuk ke birokrasi. Meski pengawasan ketat tetap dilakukan.
Indonesianis Jepang, Ken'ichi Goto mencatat perubahan kebijakan Jepang di Indonesia dalam artikelnya ''Caught in the Middle: Japanese Attitudes toward Indonesian Independence in 1945'' yang terbit di 'Journal of Southeast Asian Studies' (1996). Dua gambaran penting dalam perubahan kebijakan ini. Pertama, sikap Mayor Jenderal Yamamoto Moichiro, kepala staf angkatan ke-16 AD Jepang di Jakarta. Dalam buku hariannya yang diterbitkan di Tokyo tahun 1979, Yamamoto menulis seluruh perwira Jepang terdiam begitu 15 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat.
Kedua, dalam catatan arsip pribadinya yang kemudian diterbitkan di Tokyo pada tahun 1977, mantan pejabat sipil kantor kedinasan luar-negeri yang ditempatkan di Jakarta, Saito Shizuo, menyebut begitu pahit penyerahan tanpa syarat itu. Sebagai kepala seksi perencanaan pemerintahan militer Jepang, Shizuo tentu telah merasakan dinamika kesehariannya ikut membantu berbagai persiapan hari-hari pasukan Jepang, termasuk dalam mempersiapkan pasukan PETA.
Dari fakta-fakta sejarah kita bisa melihat, bahwa penataan birokrasi modern meski sarat diskriminasi berlangsung selama masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Termasuk, penataan birokrasi secara modern di kota Surabaya. Sedangkan mobilisasi massa berujung pembentukan badan-badan semimiliter atau militer yang melibatkan pemuda, terjadi pada masa pendudukan Jepang.
''Urban Warfare'' di Surabaya
Situasi menjelang akhir tahun 1945 di kota Surabaya sebenarnya sudah menunjukkan tanda-tanda ''Urban Warfare''. Jika kita merujuk pendefinisian istilah itu kepada karya gurubesar ilmu perang Universitas Warwick, Anthony King, yang bertajuk ''Urban Warfare in the Twenty First Century'' (2021), maka kita bisa melihat perang kota di Surabaya 1945 bukan sekadar perang biasa. Utamanya dari tingkat kepadatan penduduk ketika itu, jelas pertempuran di Surabaya berkategori ''Urban Warfare''.
Suhu ilmu perang Clausewitz menyatakan dalam buku klasiknya ''Perang'', bahwa perang merupakan keberlanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain. Artinya, perang merupakan tindakan dengan menggunakan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan politis. Ketika pasukan sekutu yang diboncengi NICA hadir di Tanjung Perak sejak Oktober 1945, maka kehadiran itu jelas bukan kunjungan muhibah. Bukan hendak wisata atau ingin berlibur. Kehadiran sekutu itu merupakan persiapan aksi kekerasan terorganisir untuk memulihkan kolonialisme.
Sehingga, pertempuran di Surabaya menjadi bukan sekadar pertempuran biasa, bukan sekadar bentrok fisik antara pasukan Inggris yang dibonceng NICA melawan arek-arek Suroboyo, melainkan yang terpenting juga adalah melihatnya dari perspektif lebih dalam. Ada kesadaran persiapan ''Urban Warfare'' yang sudah meluas di kalangan warga. Resistensi warga terhadap sekutu bersifat mandiri, bukan karena dipengaruhi apalagi diagitasi pihak lain.
Ada struktur mentalitas sekutu yang merasa sudah memenangkan perang dunia kedua lalu jumawa hendak mengembalikan kuasa kolonial Belanda atas Indonesia. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tentu tidak bisa diartikan serta-merta negeri dimana diduduki pasukan Jepang juga harus ikut tunduk kepada sekutu. Inggris dan Belanda sebagai representasi sekutu menggunakan logika pengembalian administrasi pemerintahan seperti sebelum masa perang dunia kedua. Yakni, kembalinya kolonialisme.
Taktik dan strategi, tulis Anthony King, perlu dirumuskan seksama sebelum ''Urban Warfare'' terjadi. Diantara taktik dan strategi itu adalah memenangkan hati dan pikiran warga dimana bakal pecah perang kota. Meraih simpati sekaligus merangkul warga menjadi lebih penting daripada menunjukkan kepongahan atau sikap adigang adigung adiguno ke hadapan warga. Sebab, sebagian besar warga kota merupakan warga melek informasi.
Disitulah sekutu keteteran menghadapi perlawanan semesta warga kota Surabaya. Sejarawan Israel Yoram Dinstein dalam paparannya bertajuk ''The Special Dimensions of Urban Warfare'' dalam buku 'Israel Yearbook on Human Rights' volume 50 (2020) menyebut urban warfare merupakan pertempuran yang intens dan berkelanjutan oleh pasukan di darat guna mengontrol pemukiman padat (kebanyakan pemukiman) secara efektif. Dan ternyata, selama akhir tahun 1945, sekutu masih kedodoran mengendalikan pemukiman kota Surabaya.
Untuk Masa Kini
Pertempuran November 1945 memang sudah berlalu. Yang tersisa adalah semangat kolektif bersumber dari kesaksian serta arsip yang ada. Melalui semangat kolektif ini, bisa menjadi peluang membentuk karakter ke-Surabaya-an. Bahwa ''Urban Warfare'' harus dimaknai lebih dari sekadar pertempuran fisik.
Kita memang kalah dalam pertempuran fisik karena persenjataan lawan lebih modern, lebih mutakhir. Namun, kita memenangkan perang. Perang bukan semata mewujud dalam pertempuran fisik, namun perang juga mengandung tujuan-tujuan politik. Dan, tujuan politik itu tercapai dengan baik. Masyarakat internasional menjadi tahu perlawanan Surabaya sangat keras karena mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa.
Saat ini dan masa mendatang, yang terpenting bukanlah hanya frasa heroik ''the battle of Surabaya'' namun bisa menuju ke ''Urban Warfare in Surabaya''. Tidak berhenti pada jargon-jargon heroik, tapi harus menuju pada pendalaman mentalitas tanpa menyerah, melek informasi, haus pengetahuan serta mengembangkan komunikasi aktif antar warga. Ala kulli hal, perang yang pernah terjadi di Surabaya menjadi sumber inspirasi melihat peta geopolitik saat ini dan mendatang.
Peneliti JPIPNetwork