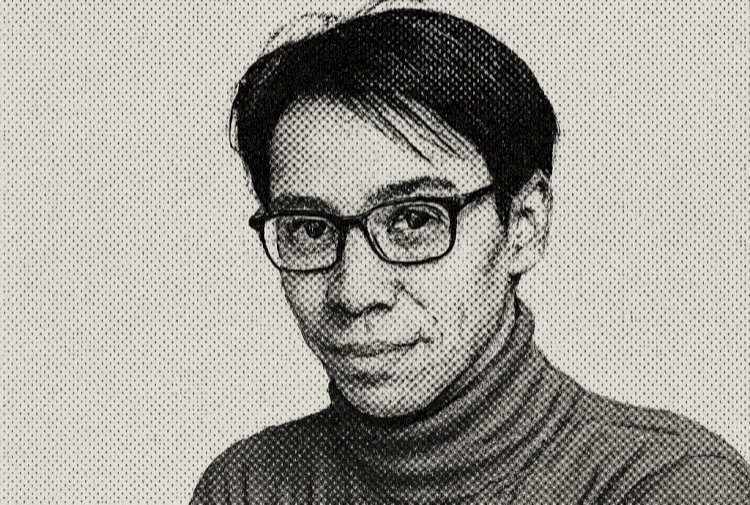SETIAP zaman melahirkan tantangan sosial-politik yang khas. Di Indonesia, salah satu tantangan kronis yang tampaknya terus membelit hingga hari ini adalah kehadiran organisasi massa (ormas) yang tumbuh secara liar dan menjelma menjadi alat tekanan sosial, bahkan lebih jauh menjadi aktor premanisme berkedok ideologi. Ironi terjadi ketika sebagian ormas mengklaim diri sebagai pelindung moral bangsa, tetapi praktik lapangan menunjukkan sebaliknya—intimidasi, kekerasan, pemalakan, dan keterlibatan dalam politik transaksional.
Pemerintah secara periodik menggembar-gemborkan upaya "pemberantasan premanisme dan ormas radikal." Namun, kebijakan tersebut acap kali menjadi polemik—baik karena selektivitas penindakan, kegamangan dalam definisi, hingga relasi kuasa yang menyelimutinya. Dalam esai ini, kita akan mengupas secara kritis akar masalah, benturan kepentingan, dan dilema struktural yang mengiringi pemberantasan ormas dan premanisme di Indonesia.
Ormas dan Premanisme: Antara Realitas dan Stereotip
Secara konseptual, ormas adalah bentuk partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Keberadaan mereka diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, sejumlah ormas justru melenceng dari misi sosial dan justru beroperasi sebagai aktor kekuasaan non-negara yang menggunakan kekerasan sebagai alat negosiasi.
Premanisme sendiri tidak bisa semata dimaknai sebagai kejahatan jalanan. Dalam makna sosiologisnya, premanisme adalah bentuk kekuasaan informal yang memanfaatkan kekerasan simbolik maupun fisik untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, politik, atau sosial. Ketika ormas menjelma menjadi kekuatan vigilante yang merasa punya hak memukul siapa pun yang mereka nilai “melanggar syariat” atau “merusak moral bangsa,” di situlah batas antara ormas dan premanisme menjadi kabur.
Negara dalam Dilema: Pelindung Demokrasi atau Pelanggeng Kekerasan?
Negara semestinya menjadi wasit netral dalam menjaga tatanan sosial dan hukum. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian ormas justru memiliki kedekatan dengan elite politik, aparat keamanan, bahkan dimobilisasi untuk kepentingan elektoral.
Ada ormas yang mendapat anggaran dari APBD dengan alasan pembinaan masyarakat, padahal aktivitasnya lebih banyak melakukan sweeping ilegal, mengintimidasi kaum minoritas, hingga berperan sebagai alat tekanan politik. Dalam hal ini, negara bukan hanya abai, tetapi turut berkontribusi dalam pelanggengan kekuasaan informal melalui ko-eksistensi dengan kekuatan ormas-preman tersebut.
Pemberantasan pun menjadi pilih-pilih: ada ormas yang dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, namun ada pula yang dibiarkan eksis meskipun terang-terangan melanggar hukum. Apakah ini bentuk konsistensi ideologis, atau sekadar seleksi politik pragmatis?
Premanisme sebagai Warisan Struktural
Tak dapat dipungkiri, premanisme di Indonesia memiliki akar historis yang dalam. Sejak masa Orde Baru, kekuasaan negara telah memelihara dan merawat preman sebagai alat kontrol sosial. Konsep “penguasa bayangan” tumbuh dalam berbagai bentuk, dari centeng pasar hingga backing proyek.
Pasca-Reformasi, kekuasaan informal ini tidak lenyap, melainkan bertransformasi. Preman hari ini lebih “modern,” memiliki struktur organisasi, seragam, bahkan legalitas formal berupa yayasan atau LSM. Mereka menjual jasa keamanan, pengawalan, bahkan menciptakan “kerusuhan” untuk kemudian menawarkan solusi damai dengan tarif tertentu.
Dalam hal ini, premanisme adalah cermin dari negara yang gagal menciptakan ketertiban sipil berbasis hukum. Ketika keadilan menjadi barang langka dan birokrasi korup, masyarakat lebih memilih bernegosiasi dengan preman daripada dengan aparat negara yang lamban atau tidak responsif.
Politik Kekerasan dalam Demokrasi Semu
Demokrasi Indonesia pasca-1998 menyisakan cacat struktural yang akut. Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi sering kali dimanipulasi menjadi alat tekanan massal. Beberapa ormas justru menikmati ruang demokrasi bukan untuk menguatkan masyarakat sipil, melainkan menjadi pelayan oligarki, pelindung bisnis ilegal, hingga perpanjangan tangan penguasa dalam meredam lawan politik.
Banyak kasus di mana ormas digunakan untuk menyerang kantor partai oposisi, merusak kegiatan diskusi, mengintimidasi mahasiswa, bahkan menduduki lahan atas nama bela agama atau bela bangsa. Premanisme dilembagakan dalam wajah populisme religius atau nasionalisme sempit, yang membius publik tapi menyayat nalar hukum.
Penegakan Hukum yang Setengah Hati
Kunci utama dalam pemberantasan ormas radikal dan premanisme adalah supremasi hukum. Namun, hukum di Indonesia sering kali bersifat transaksional. Penindakan dilakukan bukan karena pelanggaran hukum itu sendiri, tetapi karena tekanan publik, dinamika politik, atau karena ormas tersebut “sudah tidak dibutuhkan.”
Contoh konkret adalah pembubaran ormas-ormas tertentu pasca-2017, yang dilakukan dengan dalih ideologi, namun sarat muatan politik. Di sisi lain, ormas lain yang juga menggunakan kekerasan dan menyebarkan intoleransi justru dibiarkan berkembang.
Penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif justru memperkuat persepsi publik bahwa negara tidak netral. Ini menciptakan delegitimasi hukum dan menguatkan sentimen kelompok. Dalam kondisi semacam itu, premanisme tidak diberantas, tetapi hanya diganti topengnya.
Solusi Struktural: Membangun Kepastian dan Ketegasan Negara
Pemberantasan ormas liar dan premanisme tidak cukup dilakukan dengan cara represif. Pendekatan represif hanya akan memotong gejala, bukan akar. Diperlukan solusi struktural yang meliputi:
Reformasi Hukum dan Aparat Penegak Hukum
Ketegasan hukum adalah pangkal. Negara harus berani menindak semua pelaku kekerasan tanpa pandang bulu. Polisi, jaksa, dan hakim harus dilindungi dari intervensi politik agar bisa menegakkan hukum secara independen.
Rekonstruksi Peran Ormas
Ormas harus dikembalikan pada fungsinya sebagai sarana aspirasi, bukan alat tekanan. Pemerintah harus memperketat regulasi ormas, mengawasi sumber pendanaan, dan menindak tegas ormas yang melanggar hukum.
Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Premanisme tumbuh subur di tengah kemiskinan dan keterasingan sosial. Masyarakat yang putus harapan terhadap negara cenderung beralih pada kekuatan informal. Maka, pemberantasan premanisme harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik.
De-politikalisasi Aparat dan Ormas
Negara harus memisahkan secara tegas peran politik dan keamanan. Tidak boleh ada lagi aparat yang menjadi pembina ormas atau politisi yang menyewa ormas untuk keperluan elektoral.
Kasus Internasional dan Pelajaran untuk Indonesia
Beberapa negara telah menghadapi persoalan serupa. Di Amerika Latin, seperti di Brasil atau Kolombia, premanisme berbentuk geng bersenjata yang juga menjadi bagian dari sistem politik. Di India, organisasi berbasis agama atau etnis juga sering menjelma menjadi kekuatan vigilante.
Namun di negara-negara yang berhasil mengurangi kekuatan preman seperti Jepang atau Jerman, kuncinya ada pada integritas aparat, ketegasan hukum, dan pendidikan kewarganegaraan. Jepang, misalnya, pernah mengalami dominasi yakuza, namun berhasil ditekan dengan kombinasi penindakan tegas dan pendekatan ekonomi.
Pelajaran penting adalah bahwa kekuasaan informal hanya bisa dikalahkan oleh negara yang kuat secara etika dan struktur. Negara yang rapuh dan terjebak dalam patronase tidak akan mampu menghapus premanisme; mereka justru akan memanfaatkannya.
Menyikapi Polemik: Jangan Terjebak pada Romantisme atau Stigmatisasi
Polemik tentang pemberantasan ormas dan premanisme sering kali terjebak dalam dua ekstrem: romantisme sejarah dan stigmatisasi ideologi. Sebagian masyarakat membela ormas tertentu karena dianggap bagian dari sejarah perjuangan, padahal relevansi dan peran mereka hari ini jauh melenceng dari akar sejarahnya.
Sebaliknya, ada pula yang langsung menuduh semua ormas sebagai biang kerusuhan dan radikalisme, tanpa melihat peran positif sebagian kecil ormas yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang universal dan objektif sangat diperlukan: menilai ormas dari tindakannya, bukan dari label atau sejarahnya.
Pemberantasan ormas liar dan premanisme bukan sekadar agenda hukum, tetapi ujian moral dan politik negara. Apakah negara benar-benar berpihak pada keadilan dan kepastian hukum, atau hanya bermain pada narasi sesaat demi stabilitas kekuasaan?
Sebagai warga negara, kita pun harus kritis. Demokrasi tidak akan sehat jika ruang publik dipenuhi oleh kekuatan vigilante dan aparat yang permisif. Pemberantasan premanisme harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar jargon musiman. Negara harus hadir secara adil, tegas, dan bertanggung jawab. Bila tidak, premanisme akan terus beranak-pinak dalam berbagai rupa—dari gang sempit sampai ruang rapat parlemen.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news