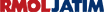 Insiden penyerangan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, Semarang dan kemudian merembet ke kerusuhan Manokwari, sebenarnya tidak perlu terjadi dan bisa diakhiri jika pemimpin Indonesia piawai mengadopsi cara penyelesaian konflik Aceh.
Insiden penyerangan asrama mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, Semarang dan kemudian merembet ke kerusuhan Manokwari, sebenarnya tidak perlu terjadi dan bisa diakhiri jika pemimpin Indonesia piawai mengadopsi cara penyelesaian konflik Aceh.
- Silaturahim Kebangsaan, PKS Jatim Kunjungi Gerindra dan Siap Beri Kontribusi Terbaik di Jawa Timur
- Masa Tenang, Menantu Jokowi Pimpin Turunkan APK Capres
- Partai Perindo Lolos Verifikasi Faktual KPU Ponorogo
"Semua kompleksitas permasalahan Papua tergantung kepiawaian pemimpinnya menerapkan konsep Aceh dulu dan Papua kini. Konflik Aceh bisa diselesaikan, kenapa Papua tidak. Toh keduanya tidak jauh beda,†terang Untung.
Menurut Untung, untuk menyelesaikan konflik Papua tidak bisa dilihat secara parsial. Artinya, masalah Papua harus dipahami dulu faktanya. Sebab yang namanya rententan insiden pasti memiliki akar permasalahan.
Dalam kajiannya, Untung Suropati menjelaskan ada lima akar permasalahan di Papua.
Pertama, pro-kontra sejarah integrasi, status politik dan identitas politik Papua. Di sini akar masalah pertama adalah debat sejarah integrasi, status politik dan identitas politik Papua karena perbedaan cara pandang yang diametral antara kaum nasionalis Indonesia dan nasionalis Papua.
"Kaum nasionalis Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa proses integrasi adalah Papua bebas dari cengkraman Belanda. Tapi tidak demikian dengan kaum nasionalis Papua. Mereka menganggap integrasi merupakan kolonisasi Indonesia,†kata Untung.
Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM. Transisi rezim dari Orde Lama ke Orde Baru tahun 1968, praktis mengubah pula pola pendekatan dan strategi pengelolaan Papua. Pada masa Orde Baru, kehadiran negara direpresentasikan militer. Akibatnya, setiap aksi protes yang dilakukan rakyat Papua terhadap kebijakan negara yang tidak sesuai dihadapi dengan pendekatan keamanan. Apalagi gerakan separatisme yang terang-terangan dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Walaupun Orde Baru telah runtuh dan pengaruhnya memudar, tapi karakteristiknya sebagai rezim militeristik yang bercirikan cara-cara kekerasan terhadap rakyat Papua di daerah tertentu masih sangat kental,†urai mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AL masa jabatan 2011-2014 ini.
Untung mencontohkan, setiap operasi militer yang digelar untuk menumpas aksi separatisme pasti dipersoalkan kalangan LSM dan gereja. Yah, pengiriman pasukan selalu menjadi opsi pertama untuk merespons indikasi apapun yang mengarah pada gerakan separatisme.
Begitu juga perjuangan politik menuntut kemerdekaan Papua, kini diambil alih kaum intelektual dan tokoh-tokoh gereja. Sementara sikap pemerintah cenderung statis. Akibatnya pola pendekatan dan strategi penanganan yang diterapkan tidak mengalami perubahan berarti.
Ketiga, kegagalan pembangunan Papua. Sejak disahkannya UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua, ternyata tidak menjamin keberhasilan pembangunan rakyat Papua.
Bahkan konflik kepentingan para amber (kaum pendatang), diskriminasi kebijakan, serta eksploitasi budaya dan sumber daya alam Papua semakin melebar.
"Dalam urusan pendidikan saja, Indonesia sudah gagal mencetak guru SD di Papua. Jangankan mencetak guru, pendidikan rakyat Papua sangat rendah,†lanjut Untung.
Tahun 2005 tingkat buta huruf masyarakat Papua mencapai 410.000 orang. Sementara rata-rata lama sekolah tahun 2003 hanya mencapai enam tahun. Dengan kata lain, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Papua hanya setingkat Sekolah Dasar.
Demikian pula dengan kondisi kesehatan di Papua. Sangat buruk. Bulan Januari 2003 tercatat 1.400 orang Papua mengidap HIV/AIDS. Tidak heran proporsi penduduk Papua yang hanya1% dari total penduduk Indonesia, tapi angka penderita HIV/AIDS mencapai 30% dari total penderita HIV/AIDS seluruh Indonesia tahun 2004.
"Dengan kata lain, posisi penduduk asli Papua berada dalam posisi termarjinalkan. Indonesia gagal melindungi rakyat Papua,†lanjutnya.
Keempat, inkonsistensi kebijakan Jakarta (Otsus). Lahirnya UU No. 21/2001 tentang Otsus yang awalnya berjalan alot, penuh liku, dan dramatis, rupanya membuat pemerintah melakukan pengingkaran komitmen yang dibuatnya sendiri. Inkonsistensi tersebut memantik munculnya beragam persoalan dan menambah pelik permasalahan.
Dijelaskan Untung, persoalan baru masa Otsus pasca-berlakunya UU No. 45/1999, antara lain penyalahgunaan anggaran; tidak tersalurkannya aspirasi orang Papua melalui MRP; meningkatnya libido pemekaran provinsi/kabupaten; dan meningkatnya potensi konflik horizontal berlatar belakang suku dan agama. Dalam jangka pendek persoalan tersebut memang tidak muncul ke permukaan, tapi untuk jangka panjang dipastikan akan menjadi sumber konflik baru.
Model-model pemekaran seperti inilah, tandas Untung, diduga hanya menguntungkan segelintir elite lokal yang menduduki jabatan, SDM luar daerah, dan pengusaha pendatang. Persoalan lain adalah munculnya konflik horizontal sesama orang Papua karena agama. Seperti demonstrasi penolakan pembangunan Masjid Raya Manokwari tahun 2005 dan pembangunan kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura tahun 2008.
Kelima, efektivitas strategi penanggulangan gangguan keamanan. Kehadiran aparat keamanan adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat dan menjaga stabilitas keamanan. Namun bagi rakyat Papua, kehadiran aparat keamanan identik dengan perampasan hak dan penindasan.
Kekerasan di Papua secara umum terbagi dalam tiga gelombang. Pertama, kekerasan tahun 1961-1969. Ini adalah babak awal hadirnya kekuasaan Indonesia di Papua. Kekerasan tak terhindarkan akibat operasi militer dalam rangka misi penyusupan (infiltrasi) Operasi Trikora dan konsolidasi kekuatan untuk menggalang dukungan menjelang Pepera tahun 1969.
Kedua, kekerasan dalam rangka mempertahankan kehadiran Indonesia yang berlangsung antara tahun 1970-1977. Kekerasan ini bertujuan untuk meredam perlawanan terhadap hasil Pepera dan menyiapkan keamanan menyambut kehadiran PT Freeport Indonesia di Papua. Selain itu juga untuk memastikan kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 dan 1977.
Ketiga, kekerasan yang identik dengan masa berlakunya Daerah Operasi Militer (DOM) antara tahun 1978-1998. Ciri khas kekerasan selama 20 tahun masa DOM adalah meluasnya kekerasan hingga ke kampung-kampung dengan dalih membasmi OPM. Pada masa DOM inilah diduga kuat telah terjadi banyak pelanggaran HAM.
Kelima akar masalah Papua, menurut Untung, harus dipahami secara mendalam. Penyelesaian bisa dilakukan secara komprehensif, integral dan holistik (KIH).
"Konflik Papua harus diselesaikan secara damai, adil dan bermartabat. Sehingga dapat menghasilkan proses inklusif yang berkembang secara mutual. Penyelesaian konflik Aceh bisa dijadikan acuan bagaimana merumuskan solusi antara Jakarta dan Papua, sekaligus merumuskan jalan keluarnya. Seperti dialog Pemerintah Indonesia dan GAM yang melahirkan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2015,†tandas Untung.
Selain itu yang paling utama, tegas Untung, konflik Papua bisa diakhiri dengan cara membuat kesepakatan antara elite Jakarta dan Papua untuk menyusun Undang-Undang baru guna memperbaiki UU No. 21/2001 tentang Otsus yang pincang, bahkan dianggap mati oleh orang Papua.
"Selama ini hubungan Jakarta-Papua terhalang ‘tembok tebal’ adanya konstruksi sejarah. Ini harus diakhiri dengan dialog dan membuat kesepakatan, salah satunya menyusun Undang-Undang baru. Tidak diragukan lagi provinsi paling timur Indonesia memerlukan lahirnya Undang-Undang baru seperti UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh,†demikian Untung Suropati.[aji
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Hasan Aminuddin Jadi Saksi Pelantikan Pelajar Nahdlatul Ulama
- Jokowi Setuju Pemilu Serentak Digelar April 2024
- DPC PKB dan Gerindra Siapkan Kader untuk Duduki Pimpinan DPRD Jember





