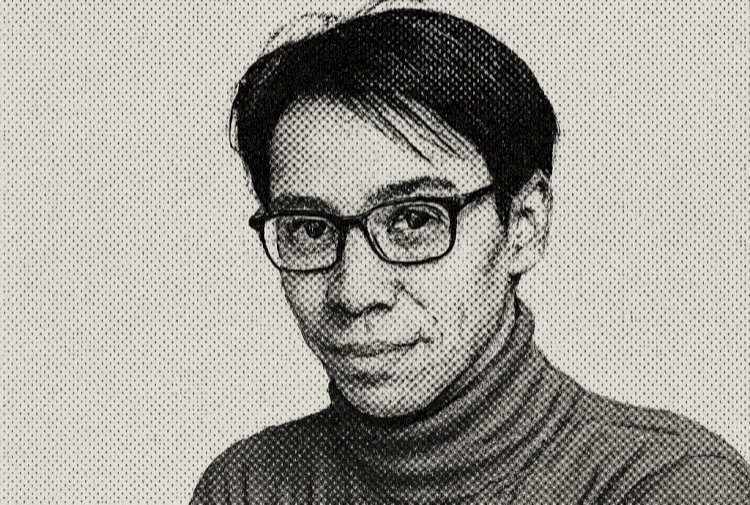- Demokrasi Dalam Genggaman Para Penjilat
- Praktik Prostitusi di Tretes yang Semakin Meresahkan
- Di Tengah Polemik Pemberantasan Ormas dan Premanisme
DALAM dunia pendidikan, simbol dan seremoni sering kali menjadi lebih penting daripada substansi. Wisuda tingkat SMA—dengan segala kemewahan toga, panggung, dan pesta foto keluarga—telah lama menjadi tradisi yang tak tergoyahkan. Namun, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk menghapuskan acara wisuda bagi siswa SMA, publik terbelah antara yang sentimental dan yang rasional. Apakah ini sebuah keputusan yang bijak? Ataukah ini hanya langkah pemiskinan tradisi? Tulisan ini mencoba mengurai persoalan dengan pendekatan kritis, tajam, mendidik, dan tetap berpijak pada universalitas nilai pendidikan.
Sejarah dan Evolusi Wisuda di Tingkat SMA
Wisuda di tingkat SMA bukanlah praktik universal. Di banyak negara maju, seremoni kelulusan hanya dilakukan di tingkat universitas, yang memang menandai berakhirnya fase pendidikan formal yang lebih panjang dan kompleks. Di Indonesia, budaya wisuda SMA mulai marak sejak awal 2000-an, bersamaan dengan komersialisasi pendidikan dan meningkatnya kelas menengah urban. Toga menjadi simbol status sosial, bukan lagi capaian akademik murni.
Sebagai bagian dari proses industrialisasi pendidikan, wisuda SMA kerap dikemas dalam bentuk pesta pora yang menguras kantong orang tua dan mempertegas kesenjangan sosial. Ironisnya, banyak siswa yang tidak melanjutkan kuliah setelah SMA, namun tetap dirayakan seolah sudah mencapai puncak keberhasilan.
Pendidikan Sebagai Proses, Bukan Seremoni
Dalam paradigma pendidikan modern, pembelajaran dipandang sebagai proses panjang, berkelanjutan, dan tak selalu membutuhkan seremoni. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan. Ketika pendidikan dipersempit dalam simbol-simbol seremoni, kita mengkhianati semangat pembebasan itu.
Lebih jauh lagi, wisuda SMA memperkuat pola pikir bahwa pendidikan adalah tujuan akhir, bukan proses transformatif. Padahal, dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan belajar terus-menerus (lifelong learning) jauh lebih penting daripada seremoni satu hari.
Komersialisasi Pendidikan dan Industri Toga
Salah satu kritik tajam terhadap wisuda SMA adalah industrialisasi seremoni ini. Sekolah-sekolah, dalam kolaborasi diam-diam dengan vendor toga, fotografer, bahkan event organizer, menjadikan wisuda sebagai ladang bisnis. Biaya yang dibebankan ke orang tua tidak tanggung-tanggung: mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Dalam masyarakat kelas menengah bawah, hal ini menjadi beban psikologis sekaligus ekonomi. Orang tua merasa berdosa jika tak mampu mengikutsertakan anaknya dalam seremoni kelulusan. Di sinilah pendidikan berubah wujud menjadi pasar: nilai pendidikan direduksi menjadi kemampuan membeli pengalaman simbolik.
Dampak Psikologis dan Ketimpangan Sosial
Penghapusan wisuda SMA bisa dilihat sebagai upaya mengembalikan esensi pendidikan sekaligus bentuk keadilan sosial. Dalam psikologi pendidikan, kompetisi sosial yang tidak sehat dapat menimbulkan stres, rendah diri, hingga krisis identitas pada siswa dari kalangan kurang mampu.
Bayangkan seorang siswa dari keluarga miskin yang tidak ikut wisuda karena tak mampu membayar toga dan biaya acara. Apakah ia lantas kurang berhasil? Apakah keberhasilan akademiknya menjadi tidak sah hanya karena absen dari seremoni? Kebijakan penghapusan wisuda adalah tamparan simbolik terhadap glorifikasi palsu yang menyamarkan ketimpangan sosial.
Mengembalikan Pendidikan ke Akar Filosofisnya
Ki Hadjar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah pembentukan karakter dan budi pekerti, bukan sekadar seremoni. Dalam konteks ini, penghapusan wisuda SMA adalah langkah menuju pemurnian tujuan pendidikan nasional: mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memperkaya vendor toga.
Dengan menghapus seremoni, sekolah justru punya ruang untuk menciptakan momen reflektif dan dialogis yang lebih bermakna—misalnya, diskusi terbuka antara siswa, guru, dan orang tua tentang perjalanan pendidikan, tantangan masa depan, dan nilai-nilai hidup.
Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
Pendekatan ilmiah terhadap kebijakan pendidikan mengharuskan kita mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan. Jika sebuah seremoni justru memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, maka itu bukan bagian dari pendidikan sejati. UNESCO dalam laporan Education for All menyebutkan bahwa akses dan partisipasi dalam pendidikan harus bebas dari diskriminasi ekonomi dan sosial.
Menghapus wisuda SMA bukan berarti menghilangkan penghargaan terhadap siswa. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghormatan yang lebih jujur—dengan memberikan semua siswa hak yang sama untuk diakui tanpa harus membayar mahal untuk sebuah seremoni.
Transformasi Kultural dan Perlawanan Emosional
Tentu saja, setiap perubahan kebijakan yang menyentuh ranah kultural akan mendapat resistensi. Banyak orang tua dan siswa yang merasa kehilangan momen kebanggaan. Namun, seperti kata Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, perubahan paradigma selalu diiringi pertentangan. Kebijakan ini adalah panggilan untuk membongkar romantisme semu dan menggantinya dengan realitas baru yang lebih jujur.
Budaya baru bisa dibentuk. Jika sebelumnya kebanggaan ditandai dengan pose toga dan background bunga, kini bisa diganti dengan portofolio capaian siswa, testimoni reflektif, atau karya kolektif sebagai bentuk perayaan non-materialistik.
Alternatif Perayaan yang Lebih Substansial
Alih-alih seremoni formal, sekolah bisa menyelenggarakan "festival pembelajaran," pameran karya siswa, atau talkshow inspiratif. Ini memberi ruang bagi siswa untuk menunjukkan capaian nyata—bukan sekadar mengenakan toga pinjaman. Dalam pendekatan konstruktivis, pembelajaran terjadi paling efektif ketika siswa aktif, bukan pasif menunggu namanya dipanggil di panggung.
Pendidikan harus berorientasi masa depan. Seremoni bisa berubah, bahkan dihapus, tapi semangat belajar dan capaian nyata siswa harus terus tumbuh. Justru di era digital ini, penghargaan bisa lebih inklusif lewat media sosial, platform online, dan jejaring yang lebih luas dari sekadar aula sekolah.
Peran Guru dan Sekolah dalam Transisi Paradigma
Perubahan paradigma ini memerlukan peran aktif guru sebagai agen perubahan. Guru harus menjadi fasilitator transisi budaya pendidikan dari simbolik ke substantif. Sosialisasi kepada orang tua, pembekalan nilai kepada siswa, dan penciptaan ruang dialogis adalah langkah strategis.
Sekolah juga perlu mendefinisikan ulang "kelulusan." Bukan sekadar lulus ujian, tetapi juga lulus dari kebodohan struktural, lulus dari budaya konsumtif, dan lulus dari ketergantungan pada validasi eksternal.
Pendidikan yang Membebaskan, Bukan Menggiring
Paradigma baru pendidikan menolak seremoni yang bersifat konsumtif dan simbolik tanpa substansi. Menghapus wisuda SMA bukan tindakan anti-tradisi, melainkan bentuk koreksi terhadap tradisi yang telah kehilangan makna. Pendidikan adalah proses pembebasan, bukan penggiringan massal ke panggung simbolik.
Saat SMA tak lagi layak dirayakan dengan toga dan karangan bunga mahal, bukan berarti pendidikan berhenti memberi makna. Justru di situlah kita mulai memahami bahwa esensi belajar adalah pertumbuhan, bukan pengakuan formal. Dengan menghapus wisuda, kita menghapus topeng pendidikan palsu, dan membuka jalan menuju sistem pendidikan yang jujur, adil, dan manusiawi.
Catatan: Tulisan ini ditujukan sebagai refleksi kritis terhadap kebijakan pendidikan, bukan serangan terhadap tradisi. Penulis percaya bahwa setiap kebijakan harus ditimbang dengan akal sehat, empati sosial, dan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan.
*Pengarang novel, pemerhati sosial dan budaya, esais, dan cerpenis
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Demokrasi Dalam Genggaman Para Penjilat
- Praktik Prostitusi di Tretes yang Semakin Meresahkan
- Di Tengah Polemik Pemberantasan Ormas dan Premanisme